Sabtu, 24 Oktober 2009 | 03:29 WIB
Saat mendarat hari Sabtu terakhir Oktober 2008 di Bandara O’Hare, Chicago, AS, embusan angin menusuk tulang. Baju monyet, kaus dalam, kemeja, jaket, syal, kaus tangan, dan topi masih belum cukup menangkal rasa dingin. Temperatur hari itu 11 derajat celsius dan diperkirakan makin anjlok pada hari-hari berikutnya.
Cuaca tak nyaman itu tak menghalangi ribuan warga dari mancanegara yang datang menghadiri Election Night di Grant Park. Kapan lagi ikut pesta merayakan kemenangan Barack Obama? Apalagi, pada hari itu Obama telah mendapat julukan ”suci” yang tak sengaja diucapkan John McCain, ”The One” (Sang Terpilih).
Mungkin alam mencintai Obama, ramalan cuaca ternyata keliru. ”Indian Summer” datang tiba-tiba. Senin 3 November, atau sehari sebelum Election Night, temperatur malah naik ke 20-an derajat celsius. Matahari menampakkan senyum hangat.
”Obama dipilih rakyat dan juga direstui alam,” kata orang-orang. Keesokan harinya Grant Park disesakkan 600.000 orang sejak petang. Padahal, kepastian kemenangan Obama baru diketahui sekitar pukul 22.30 waktu setempat.
Saat monitor raksasa mengumumkan kemenangan Obama, gendang telinga seperti pecah. Anda bahkan tak bisa mendengarkan suara sendiri. Untuk pertama kalinya saya menyaksikan puluhan—mungkin ratusan—orang ”
Waktu menghadiri pelantikan Obama di halaman Kongres di Washington DC medio Januari, cuaca mencapai minus 10 derajat celsius ditambah
Rencana pemain
Suasana di Grant Park jauh lebih akrab dibandingkan dengan di Kongres. Di Grant Park menyampaikan pidato kemenangan, di Kongres ia berpidato sebagai presiden yang berdiri di atas semua golongan. Di Grant Park semua orang melepas emosi, di Kongres tiap orang berlaku khidmat.
Mengapa jutaan manusia dari berbagai pelosok Amerika Serikat dan mancanegara mau melakukan perjalanan spiritual menghadiri Election Night dan pelantikan Obama? Mengapa mereka menantang cuaca dan menyisihkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menjadi saksi sejarah?
Pertama, Obama bukan politisi biasa. Ia memulai karier sejak usia awal 20 tahunan dengan niat dan tekad pengabdian yang melebihi politik semata-mata. Ia menjalani
Ia mengurusi remaja yang terjangkit narkoba, selokan mampat, kaum minoritas, sampai menggalang demo. Ia bukan John F Kennedy atau George W Bush yang beruntung lahir dari kalangan ”darah biru” politik yang sejak dini disiapkan mengabdi pada pemerintahan.
Kedua, ia mampu menjalani politik pengabdian berkat latar belakang moral, keyakinan ideologis, pendidikan formal, dan pengalaman organisasional memadai. Siapa pun, termasuk Obama, mengubah jalan hidup dari profesor di kampus menjadi politisi ibarat membalikkan telapak tangan belaka.
Selama melakoni proses pematangan politik tanpa melupakan pengabdian, selama tidak kehilangan moral, dan selama teguh dengan keyakinan politik, cepat atau lambat Anda akan berhasil membangun karisma. Itulah Obama yang sempat mengalami kesepian yang amat menyiksa karena mengabaikan kehidupan pribadinya demi politik.
Ketiga, sebagai minoritas, ia simbolisasi dari ”mimpi Amerika” yang pasti juga didambakan kita. Ia menjadi presiden kulit hitam pertama bukan karena mayoritas rakyat Amerika Serikat menganggap waktunya telah tiba, tetapi karena prestasinya sebagai politisi pengabdi. Pendek kata, tidak ada faktor kebetulan yang mendongkrak Obama.
Itu sebabnya ia dijuluki ”Sang Terpilih”. Justru saat situasi internasional abad ke-21 inilah dunia memerlukan Obama. Seperti kata mantan diplomat Makarim Wibisono, dunia pasca-Perang Dingin ini memasuki era
Tanpa harus dibahas lagi, dengan sendirinya universalisme yang diperjuangkan Obama tentu saja kesetaraan. Tidak mudah bagi seorang presiden AS untuk mengulurkan tangan kepada Presiden Venezuela Hugo Chavez, membuka dialog dengan Iran meski hubungan diplomatik belum terjalin, atau melawat ke China.
Cepat atau lambat, rezim komunis di Pyongyang akan membuka diri. Sudah ada pertanda baik Iran siap berdialog tentang program nuklirnya dengan Obama lewat IAEA. Obama juga membatalkan rencana menggelar sistem rudal pertahanan di Eropa, langkah yang disambut sukacita Rusia.
Tiba-tiba Obama dianugerahi Nobel Perdamaian. Ada benarnya argumen Obama belum layak menerima Nobel karena belum membuktikan diri sebagai pemrakarsa perdamaian. Namun, keputusan itu diambil Komite Nobel—bukan Obama. Dengan sikap rendah hati, ia mengatakan belum layak menerima anugerah terhormat itu.
Obama menampilkan wajah AS yang lebih manusiawi. Tak mudah memperbaiki citra AS yang amburadul selama Presiden George W Bush memerintah. Ia dihujani kritik pedas, memaksanya mengubah
Setelah setahun, Obama tetap jadi harapan dunia. Sayang November ini ia batal ke Indonesia, negeri yang pernah membesarkan dia. Ia menghadiri KTT APEC di Singapura dan berkunjung ke Korsel, China, serta Jepang. Rupanya ia lebih kangen kimchi, somay, dan sushi daripada nasi goreng.












































































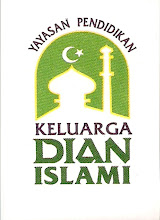
Tidak ada komentar:
Posting Komentar