
SBY membawa saya dan seluruh pembantunya ke ruang kreatifitas yang baru. Jujurnya, pada tahun 2004, saya sempat merasa mentok dengan kemampuan saya—dan hal ini memang lazim dirasakan pegawai negeri atau diplomat yang sedang puber kedua setelah puluhan tahun mengabdi.
Namun entah bagaimana, Presiden SBY mendorong saya untuk bekarya melampau batas kemampuan saya. Kemampuan saya menulis pidato, menganalisa masalah, mencari solusi, dan berpikir secara kreatif (creative thingking) melonjak tajam, dikatrol oleh Presiden SBY. Sebagai atasan, Presiden SBY terus-menerus menantang, memforsir, mendorong, membanting, menempa dan menguji saya dan pembantunya. “Tidak ada kata tidak bisa. Harus bisa!” beliau selalu mengatkan pada anak buahnya. Setiap SBY melihat saya mulai kekuarangan bensin, beliau selalu mengingatkan agar saya jangan patah semangat karena beginilah dulu sewaktu di TNI beliau ditempa untuk menjadi pemimpin.
Akibatnya, saya menemukan dimensi dan profesionalisme saya. Di sini saya menyadari bahwa aspek penting dari seorang pemimpin adalah kemampuannya untuk membuat anak buahnya tumbuh dan berkembang. Aya saya Profesor Hasyim Djalal benar sekali ketika saya mananyakan beliau dimana pos diplomatik yang paling ideal: “it’s not where your post is, it’s who your boss is.” Sehebat-hebatnya kantor kita, kalau atasan tidak mendidik dan mengayomi, kita akan sulit berkembang, dan hal ini berlaku sekali bagi pegawai yunior yang sedang tumbuh.
Saya sungguh percaya bahwa cara terbaik untuk mengembangkan diri adalah dengan mencari mentor. Ilmu yang bisa diserap dari satu mentor bisa menyamai ratusan buku dan duduk bertahun-tahun di bangku kuliah.
Sepanjang karier saya, saya mendapat berkah bisa mengenal, belajar dan bekerja dengan figur-figur yang luar biasa: Ali Alatas, Hassan Wirajuda, Wiryono Sastrohandoyo, Soemadi Brotodiningrat, Nugroho Wisnumurti, Arizal Effendi, Rahardjo Jamtono, Dorodjatun Kuntyoro-jakti, dan ayah saya Profesor Hasjim Djalal. Setiap figur ini melatih dan menggembleng saya menjadi diplomat yang lebih baik.
Dalam diri SBY, saya menemukan mentor yang tidak ada bandingannya, karena cakrawala yang dibuka bukan hanya diplomasi namun seluruh aspek kehidupan bangsa. SBY memaksa saya untuk melihat segala permasalahan dari segala sisi, dari berbagai kepentingan dengan semua dimensinya. Di bawah SBY, saya tidak bisa berpikir hanya sebagai diplomat, namun harus mempertimbangan konteks yang lebih luas. SBY juga mengajar saya bahwa politik itu identik dengan kebaikan, bukan kekuasaan—penguasa yang mengagungkan kekuasaan tanpa moralitas dan etika akan mencelakakan diri sendiri dan rakyat. SBY juga melatih anak-buahnya untuk tidak pernah merasa puas atau terbuai dengan prestasi hari ini dan selalu introspeksi diri. Di sini, ruangan kelas saya adalah rapat-rapat Kabinet dan Staf Khusus, dan juga—favorit saya—berbagai kesempatan makan siang dengan SBY dimana beliau dengan santai mengupas masalah dengan terbuka, membahas suatu ide baru yang beliau baru dengar, atau menyampaikan pandangan beliau mengenai suatu kejadian.
Pengalaman membantu SBY dari dekat juga membuat saya yakin mengani satu hal : seorang pemimpin bangsa mutlak harus mempunyai kepedulian intelektual (intelektual curiosity)—atau sifat ingin tahu. Kalau seorang pemimpin yidak ada rasa ingin tahu, ia tidak akan peduli. Kalau ia tidak peduli, ia tidak akan bertanya. Kalau ia tida bertanya, ia tidak akan mendapat jawaban. Kalau tidak ada jawaban, ia tidak akan ada solusi. Dan kalau tidak ada solusi, ia bukan pemimpin. Dalam menjalankan roda pemerintahan, rasa ingin tahu inilah yang akan membuat seorang pemimpin terus berkembang, kreatif dan efektif.
Intellectual curiosity SBY ini sudah menjadi rahasia umum. Ruang kerja beliau di Istana Negara dan di kediaman beliau di Cikeas penuh dengan buku-buku yang beraneka ragam dan judul di berbagai sudut. Kalau Menteri-menteri bepergian ke Luar Negeri, sudah menjadi “SOP” bahwa kalau mau memberikan oleh-oleh kepada Presiden SBY biasanya berupa satu atau dua buku yang paling mutahir. Dan kalau SBY bepergian ke Luar Negeri, beliau selalu meminta waktu luang untuk mampir ke toko buku setempat. SBY juga selalu membaca artikel-artikel dan studi penting yang saya suguhkan secara berkala kepada beliau. Favorit beliau adalah: “Mapping the Global Future” karya National Intelligence Council, “The End of Poverty” karya Jeffrey Sachs, “Reinventing Government for the Twenty-First Century” editor Rondinelli dan Cheema, “Globalization and Its Discontents” karya Stiglitz, “Soft Power” karya Joseph Nye, Jr, dan “The New Asian Hemisphere” karya Kishore Mahbubani.
Saya pribadi juga sangat merasakan manfaat dari intelektualitas SBY. Ketika saya baru masuk Istana, saya membentuk apa yang dinamakan “policy brainstorming forum”---suatu forum diskusi bebas yang dihadiri pejabat tinggi, pakar dan opinions leaders untuk membahas topik-topik khusus. Dari forum ini, saya dapat mengumpulkan banyak masukan dan analisa untuk hal-hal yang menjadi perhatian Presiden SBY. Presiden SBY pernah dua kali muncul di acara policy brainstorming sessions ini secara mendadak, yakni ketika membahas mengenai Myanmar, dan Islam dan barat. Saya sendiri sempat terperanjat karena diskusi mengenai Myanmar dilakukan di sebuah ruangan kumuh di lantai dua gedung biro pers, dan SBY harus berjalan kaki lumayan jauh dari kantornya. Ketika Paspampres datang, saya meminta hadirin bangun untuk menyambut Presiden SBY, namun tidak ada yang berdiri karena menyangka saya bergurau. Presiden SBY langsung masuk, menyapa para peserta diskusi yang kaget melihat Presiden SBY, dan ikut menyampaikan pandangannya dalam brainstorming yang hangat.
Dalam membantu Presiden SBY, saya dan staf lainnya tidak lepas dari blunder. Istana penuh dengan cerita-cerita lucu mengenai berbagai blunder yang dilakukan oleh staf Presiden, dan mungkin suatu hari akan ada buku khusus mengenai topik ini. (Bersambung)
Namun entah bagaimana, Presiden SBY mendorong saya untuk bekarya melampau batas kemampuan saya. Kemampuan saya menulis pidato, menganalisa masalah, mencari solusi, dan berpikir secara kreatif (creative thingking) melonjak tajam, dikatrol oleh Presiden SBY. Sebagai atasan, Presiden SBY terus-menerus menantang, memforsir, mendorong, membanting, menempa dan menguji saya dan pembantunya. “Tidak ada kata tidak bisa. Harus bisa!” beliau selalu mengatkan pada anak buahnya. Setiap SBY melihat saya mulai kekuarangan bensin, beliau selalu mengingatkan agar saya jangan patah semangat karena beginilah dulu sewaktu di TNI beliau ditempa untuk menjadi pemimpin.
Akibatnya, saya menemukan dimensi dan profesionalisme saya. Di sini saya menyadari bahwa aspek penting dari seorang pemimpin adalah kemampuannya untuk membuat anak buahnya tumbuh dan berkembang. Aya saya Profesor Hasyim Djalal benar sekali ketika saya mananyakan beliau dimana pos diplomatik yang paling ideal: “it’s not where your post is, it’s who your boss is.” Sehebat-hebatnya kantor kita, kalau atasan tidak mendidik dan mengayomi, kita akan sulit berkembang, dan hal ini berlaku sekali bagi pegawai yunior yang sedang tumbuh.
Saya sungguh percaya bahwa cara terbaik untuk mengembangkan diri adalah dengan mencari mentor. Ilmu yang bisa diserap dari satu mentor bisa menyamai ratusan buku dan duduk bertahun-tahun di bangku kuliah.
Sepanjang karier saya, saya mendapat berkah bisa mengenal, belajar dan bekerja dengan figur-figur yang luar biasa: Ali Alatas, Hassan Wirajuda, Wiryono Sastrohandoyo, Soemadi Brotodiningrat, Nugroho Wisnumurti, Arizal Effendi, Rahardjo Jamtono, Dorodjatun Kuntyoro-jakti, dan ayah saya Profesor Hasjim Djalal. Setiap figur ini melatih dan menggembleng saya menjadi diplomat yang lebih baik.
Dalam diri SBY, saya menemukan mentor yang tidak ada bandingannya, karena cakrawala yang dibuka bukan hanya diplomasi namun seluruh aspek kehidupan bangsa. SBY memaksa saya untuk melihat segala permasalahan dari segala sisi, dari berbagai kepentingan dengan semua dimensinya. Di bawah SBY, saya tidak bisa berpikir hanya sebagai diplomat, namun harus mempertimbangan konteks yang lebih luas. SBY juga mengajar saya bahwa politik itu identik dengan kebaikan, bukan kekuasaan—penguasa yang mengagungkan kekuasaan tanpa moralitas dan etika akan mencelakakan diri sendiri dan rakyat. SBY juga melatih anak-buahnya untuk tidak pernah merasa puas atau terbuai dengan prestasi hari ini dan selalu introspeksi diri. Di sini, ruangan kelas saya adalah rapat-rapat Kabinet dan Staf Khusus, dan juga—favorit saya—berbagai kesempatan makan siang dengan SBY dimana beliau dengan santai mengupas masalah dengan terbuka, membahas suatu ide baru yang beliau baru dengar, atau menyampaikan pandangan beliau mengenai suatu kejadian.
Pengalaman membantu SBY dari dekat juga membuat saya yakin mengani satu hal : seorang pemimpin bangsa mutlak harus mempunyai kepedulian intelektual (intelektual curiosity)—atau sifat ingin tahu. Kalau seorang pemimpin yidak ada rasa ingin tahu, ia tidak akan peduli. Kalau ia tidak peduli, ia tidak akan bertanya. Kalau ia tida bertanya, ia tidak akan mendapat jawaban. Kalau tidak ada jawaban, ia tidak akan ada solusi. Dan kalau tidak ada solusi, ia bukan pemimpin. Dalam menjalankan roda pemerintahan, rasa ingin tahu inilah yang akan membuat seorang pemimpin terus berkembang, kreatif dan efektif.
Intellectual curiosity SBY ini sudah menjadi rahasia umum. Ruang kerja beliau di Istana Negara dan di kediaman beliau di Cikeas penuh dengan buku-buku yang beraneka ragam dan judul di berbagai sudut. Kalau Menteri-menteri bepergian ke Luar Negeri, sudah menjadi “SOP” bahwa kalau mau memberikan oleh-oleh kepada Presiden SBY biasanya berupa satu atau dua buku yang paling mutahir. Dan kalau SBY bepergian ke Luar Negeri, beliau selalu meminta waktu luang untuk mampir ke toko buku setempat. SBY juga selalu membaca artikel-artikel dan studi penting yang saya suguhkan secara berkala kepada beliau. Favorit beliau adalah: “Mapping the Global Future” karya National Intelligence Council, “The End of Poverty” karya Jeffrey Sachs, “Reinventing Government for the Twenty-First Century” editor Rondinelli dan Cheema, “Globalization and Its Discontents” karya Stiglitz, “Soft Power” karya Joseph Nye, Jr, dan “The New Asian Hemisphere” karya Kishore Mahbubani.
Saya pribadi juga sangat merasakan manfaat dari intelektualitas SBY. Ketika saya baru masuk Istana, saya membentuk apa yang dinamakan “policy brainstorming forum”---suatu forum diskusi bebas yang dihadiri pejabat tinggi, pakar dan opinions leaders untuk membahas topik-topik khusus. Dari forum ini, saya dapat mengumpulkan banyak masukan dan analisa untuk hal-hal yang menjadi perhatian Presiden SBY. Presiden SBY pernah dua kali muncul di acara policy brainstorming sessions ini secara mendadak, yakni ketika membahas mengenai Myanmar, dan Islam dan barat. Saya sendiri sempat terperanjat karena diskusi mengenai Myanmar dilakukan di sebuah ruangan kumuh di lantai dua gedung biro pers, dan SBY harus berjalan kaki lumayan jauh dari kantornya. Ketika Paspampres datang, saya meminta hadirin bangun untuk menyambut Presiden SBY, namun tidak ada yang berdiri karena menyangka saya bergurau. Presiden SBY langsung masuk, menyapa para peserta diskusi yang kaget melihat Presiden SBY, dan ikut menyampaikan pandangannya dalam brainstorming yang hangat.
Dalam membantu Presiden SBY, saya dan staf lainnya tidak lepas dari blunder. Istana penuh dengan cerita-cerita lucu mengenai berbagai blunder yang dilakukan oleh staf Presiden, dan mungkin suatu hari akan ada buku khusus mengenai topik ini. (Bersambung)












































































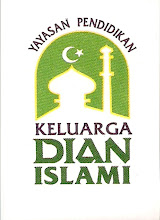
Tidak ada komentar:
Posting Komentar