
Setelah Pergi, Baru Sadari Betapa Pentingnya Rendra
PERSDA/BIAN HARNANSA/WS RENDRA/
Jumat, 7 Agustus 2009 06:06 WIB
KOMPAS.com — Duka datang berendeng menghampiri kita. Setelah pada Selasa (4/8) lalu penyanyi Mbah Surip pergi, pada Kamis malam (6/8) pukul 20.30 WIB, giliran budayawan dan penyair WS Rendra menyusul menghadap Sang Khalik.
Seperti telah saling janjian, kedua seniman yang telah mendahului kita itu menempati "rumah" abadi yang sama hanya selisih dua hari, yakni di pekarangan rumah WS Rendra di daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat.
Willybrodus Surendra Broto yang kemudian berganti nama menjadi Wahyu Sulaiman Rendra setelah dirinya Muslim, menjalani perawatan jantung sejak setahun lalu. Berkali-kali ia masuk rumah sakit, sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di kediaman salah satu putrinya, Clara Shinta, di Perumahan Pesona Kayangan, Depok, Bogor.
Sebagai pengagumnya, tentu saja saya amat sangat kehilangan dia. Gara-gara salah satu puisinya yang terangkum dalam Potret Pembangunan Dalam Puisi, saya bersikeras kepada ayah untuk tak lagi repot-repot mengongkosi kuliah saya. Saya pilih berhenti sebagai Sarjana Muda dan memulai "kuliah" di jalanan bersama para seniman, buruh-buruh pabrik di Srondol, dan gelandangan di Simpang Lima, Semarang, di pertengahan tahun 80-an. Puisi itu kurang lebih bercerita tentang pendidikan. Pendidikan kita berkiblat ke Barat. Di Barat, anak-anak dididik untuk menjadi mesin industri, sedangkan kita? Dididik untuk menjadi kuli! Wah..., jiwa muda saya yang membara pun langsung bergetar.
Jumat, 7 Agustus 2009 06:06 WIB
KOMPAS.com — Duka datang berendeng menghampiri kita. Setelah pada Selasa (4/8) lalu penyanyi Mbah Surip pergi, pada Kamis malam (6/8) pukul 20.30 WIB, giliran budayawan dan penyair WS Rendra menyusul menghadap Sang Khalik.
Seperti telah saling janjian, kedua seniman yang telah mendahului kita itu menempati "rumah" abadi yang sama hanya selisih dua hari, yakni di pekarangan rumah WS Rendra di daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat.
Willybrodus Surendra Broto yang kemudian berganti nama menjadi Wahyu Sulaiman Rendra setelah dirinya Muslim, menjalani perawatan jantung sejak setahun lalu. Berkali-kali ia masuk rumah sakit, sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di kediaman salah satu putrinya, Clara Shinta, di Perumahan Pesona Kayangan, Depok, Bogor.
Sebagai pengagumnya, tentu saja saya amat sangat kehilangan dia. Gara-gara salah satu puisinya yang terangkum dalam Potret Pembangunan Dalam Puisi, saya bersikeras kepada ayah untuk tak lagi repot-repot mengongkosi kuliah saya. Saya pilih berhenti sebagai Sarjana Muda dan memulai "kuliah" di jalanan bersama para seniman, buruh-buruh pabrik di Srondol, dan gelandangan di Simpang Lima, Semarang, di pertengahan tahun 80-an. Puisi itu kurang lebih bercerita tentang pendidikan. Pendidikan kita berkiblat ke Barat. Di Barat, anak-anak dididik untuk menjadi mesin industri, sedangkan kita? Dididik untuk menjadi kuli! Wah..., jiwa muda saya yang membara pun langsung bergetar.
AKSI SI BURUNG MERAK SAAT MEMBACA PUISI atau SAJAKNYA
 Pertama kali melihat ia membacakan puisi-puisinya di Semarang pada tahun 1985. Sungguh menggelorakan jiwa muda saya saat itu. Masih saya kenang hingga kini, bagaimana ia membawakan sajak-sajaknya dan lalu melemparkan ke udara setelah rampung dibaca. Dengan tangan terkepal meninju udara, ia melangkah membelah panggung, lantas suaranya yang parau itu pun meneriakkan judul puisi yang akan dibacakannya:
Pertama kali melihat ia membacakan puisi-puisinya di Semarang pada tahun 1985. Sungguh menggelorakan jiwa muda saya saat itu. Masih saya kenang hingga kini, bagaimana ia membawakan sajak-sajaknya dan lalu melemparkan ke udara setelah rampung dibaca. Dengan tangan terkepal meninju udara, ia melangkah membelah panggung, lantas suaranya yang parau itu pun meneriakkan judul puisi yang akan dibacakannya:Sajak Sebatang Lisong
menghisap sebatang lisong
melihat Indonesia Raya
mendengar 130 juta rakyat
dan di langit
dua tiga cukung mengangkang
berak di atas kepala mereka
matahari terbit
fajar tiba
dan aku melihat delapan juta kanak - kanak
tanpa pendidikan
aku bertanya
tetapi pertanyaan - pertanyaanku
membentur meja kekuasaan yang macet
dan papantulis - papantulis para pendidik
yang terlepas dari persoalan kehidupan
delapan juta kanak - kanak
menghadapi satu jalan panjang
tanpa pilihan
tanpa pepohonan
tanpa dangau persinggahan
tanpa ada bayangan ujungnya
Meski ia telah tampak sepuh karena usia telah menginjak lima puluh, toh sihir suara dan ekspresinya sungguh-sungguh telah menjadi racun bagi saya untuk makin dalam bergulat dengan dunia teater dan susastra.
Saya pun mulai melahap puisi-puisi karyanya. Beberapa puisinya bahkan pernah saya hafal di luar kepala. Nyanyian Angsa, itulah salah satunya. Saya pun terkesan dengan gaya bercerita Rendra yang kuat dalam kumpulan puisi Balada Orang-Orang Tercinta yang ia bukukan di pertengahan tahun 50-an. Bahasanya yang lentur dan keseharian, membuat puisi-puisinya yang getir tetap enak dinikmati.
Balada Terbunuhnya Atmo Karpo yang berkisah tentang matinya seorang perampok bernama Atmo Karpo di tangan anaknya sendiri, Joko Pandan, adalah puisi yang amat dramatik.
Dan inilah ujung puisi Balada Terbunuhnya Atmo Karpo yang selalu saya kenang,
Berberita ringkik kuda muncullahJoko Pandan
segala menyibak bagi derapnya kuda hitam
ridla dada bagi derunya dendam yang tiba
pada langkah pertama keduanya sama baja
pada langkah ketiga rubuhlah Atmo Karpo
panas luka-luka terbuka daging kelopak-kelopak angsoka
Malam bagai kodok hutan bopeng oleh luka
pesta bulan, sorak sorai, anggur darah
Joko Pandan menegak, menjilat darah di pedang
ia telah membunuh bapaknya
Hmm... saya juga tak bosan-bosannya menikmati romantisme hitam puisi Balada Ibu yang Dibunuh
Ibu musang dilindung pohon tua meliang
bayinya dua ditinggal mati lakinya.
Bulan sabit terkait malam memberita datangnya
waktu makan bayi-bayinya mungil sayang
Lalu, hingga kini.. saban kali kangen pada ibu, saya pun lantas teringat pada puisi Nyanyian Bunda yang Manis.
Kalau putraku datang
ia datang bersama bulan
kena warna jingga dan terang
adalah warna buah di badan
Wahai telor madu dan bulan!
Perut langit dapat sarapan
Ia telah berjalan jauh sekali
dan kakiknya tak henti-henti
menapaki di bumi hatiku
Ah, betapa jauh kembara burungku!
Awal tahun 90-an, saya bertemu dan berkenalan dengannya. Saya pun memanggilnya Mas Willy, sebagaimana orang-orang menyapanya. Tubuhnya yang selalu wangi, roman mukanya yang ganteng, serta tutur katanya yang terjaga dalam kecerdasan, membuat siapa pun akan menyimak hikmat tiap kali ia bicara.
Rendra bak kamus berjalan. Ia, kendati tak kelar kuliah, adalah pemikir ulung untuk urusan sejarah bangsa ini. Ia jabarkan dengan detail riwayat kekuasaan raja-raja Jawa. Ia pun paham benar mengenai kultur orang darat dan air. Saya masih ingat dengan statement dia tentang kekuasaan di negeri ini, menurutnya, dari dulu hingga kini negeri ini dikuasai oleh preman. "Anda kira siapa itu Gadjah Mada? Ken Arok, Soeharto... preman!" kata Rendra dalam sebuah diskusi.
Di Makassar pada tahun 1998, saya kian dekat dengan Rendra. Kami makan malam bersama di sebuah rumah makan dekat Pantai Losari yang menyajikan ikan bakar. Bagai tokoh kuliner, ia pun berkata, "Yang gosong jangan dibuang, itu justru yang enak. Hmmm," Rendra mengupas kulit ikan yang gosong lalu langsung mengudapnya.
Setelah itu, kami kian kerap bertemu. Kadang di rumah Setiawan Djody, atau di acara diskusi, tapi sekali-sekala saya juga menyempatkan diri datang ke kediamannya yang asri di Cipayung.
Pernah pada sebuah sore di tahun 2003, di halaman sebuah gedung pertemuan di Kota Jambi, kami bersitatap sambil bersalaman. Kala itu kami bersepakat untuk mengaku saya sebagai anaknya dan ia sebagai bapak saya.
Entah apa sebabnya tiba-tiba kesepakatan itu terjadi. Yang terang saat itu saya terharu kala melihat Rendra bicara tentang kesehatan masyarakat, terutama untuk mereka yang terkena penyakit TBC. Bukan materi pembicaraan dia yang membuat saya tertegun, tapi gerak tubuhnya yang telah lamban itulah yang membikin saya ingin melindunginya.
Saya sungguh trenyuh kala itu. Dalam hati saya berucap, inikah orang yang dulu pernah menaklukkan beribu-ribu mata dan jiwa penggemarnya ketika dirinya di panggung. Inikah orang yang dulu galak memimpin kawan-kawan demonstran melawan rezim Soeharto? Pertanyaan berjubel-jubel di kepala saya.
Begitu selesai bicara di muka forum, saya pun langsung bergegas menghampirinya seraya menuntun tangannya keluar ruangan. Di Belakang kami ada Ken Zuraida, istri Rendra, serta beberapa anak Bengkel Teater, mengiringi kami.
Di luar, seorang wartawan mencegat Rendra untuk memberitahu, sebentar nanti ada acara diskusi bersama kawan-kawan seniman Jambi. Lantaran Mba Ida, demikian Ken Zuraida biasa disapa, tak bisa mengikuti acara diskusi, ia pun meminta saya untuk mengiringi Mas Willy, "Tolong dijaga Mas Willy," kata Mba Ida sebelum kami berangkat ke acara diskusi. Sejak saat itu, saya pun kerap memanggil Mas Willy dengan sebutan Pak Rendra.
Dari Jambi kami meneruskan perjalanan ke Medan untuk acara yang sama dengan di Kota Jambi. Pak Rendra tampak kelelahan setibanya di Medan. Sebab, karena cuaca buruk, dari Jambi pesawat yang kami tumpangi harus menuju ke Jakarta lebih dahulu, sebelum akhirnya terbang ke Medan.
Di tengah-tengah road show itu, saya sempat berterus terang kepadanya, mengapakah dirinya tampak begitu letih. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia pun berterus terang bahwa dirinya bukan bapak yang baik bagi anak-anaknya, dan ia sangat ngungun karenanya.
Kini Rendra telah pergi. Ia tak cuma meninggalkan catatan-catatan susastra yang diakui komunitas sastra dunia, tapi juga pemikiran-pemikiran brilian tentang bangsa ini. Dialah yang senantiasa mengingatkan para penguasa negeri ini agar selalu berpihak kepada rakyat. Dia pula yang selalu membela orang-orang tertindas untuk bangkit.
Rendra telah berpulang. Bukan cuma ini kali kita ditinggal pergi oleh orang-orang besar macam Rendra. Sebelum Rendra ada Ali Sadikin, Soekarno, Mbah Surip, dan tokoh-tokoh lainnya. Tapi selalu saja kita tak pernah belajar bagaimana kita menghargai dan memulyakan orang-orang besar itu secara sepatutnya semasa hidupnya. Lihatlah Drs Sujadi yang menjadi tokoh Pak Raden dalam film Si Unyil itu yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk dunia anak-anak; ia masih mengontrak rumah padahal usianya telah senja. Pandanglah juga Pak Gesang yang baru diingat justru setelah orang Jepang mengingatnya. Lihatlah juga para atlet yang telah mengharumkan bangsa ini yang sebagian di antaranya hidup terlunta-lunta, dan masih banyak orang-orang besar lainnya yang dilupakan.
Sesal apa yang harus kita sesali. Rendra telah kembali menghadap Ilahi. Satunya yang sisa adalah harapan akan lahirnya Rendra Rendra baru yang sanggup menggedor ketidakadilan dengan pena dan suara. Begitulah, kita merasa kehilangan Rendra justru ketika dia telah tiada.
Jodhi Yudono . JY












































































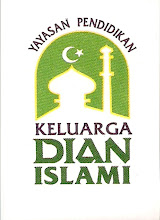
Tidak ada komentar:
Posting Komentar