Senin, 10 Agustus 2009 - 09:17
Pertama kali puisi saya diterbitkan dalam buku antologi puisi berjudul Maha Duka Aceh,diterbitkan oleh Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin pada 2005.
Pertama kali puisi saya diterbitkan dalam buku antologi puisi berjudul Maha Duka Aceh,diterbitkan oleh Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin pada 2005.
Kata pengantar buku tersebut ditulis oleh "Si Burung Merak" Wahyu Sulaiman (Willibrodus Surendra) Broto Rendra. Buku kumpulan puisi yang disebut oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai "cetusan jiwa spontan untuk mengagungkan kekuatan rakyat Aceh dalam menghadapi bencana yang dahsyat" itu berisi karya-karya penyair kondang dari seluruh pelosok Nusantara tercinta.
Tercatat nama-nama tokoh seperti Gus Mus, Danarto, Goenawan Mohamad, Ikranegara, Jose Rizal Manua, Romo Muji Sutrisno, Taufiq Ismail. Saya sungguh merasa amat tersanjung dideretkan setara dengan mereka kendati bobot jelas beda. Nah, Mas Willy, seperti biasa, menulis kata pengantar yang menohok kanan-kiri, di bawah judul "Nyanyian Matahari dari Satu Sisi: Memandang Insan dari Segenap Jurusan".
Coba kita renungkan tudingannya yang menyengat, tajam, menukik pada kenyataan yang menyakitkan: Partai-partai politik tak pernah mengindahkan kepentingan rakyat di bawah karena mereka hanya sibuk dengan politik golongan dan politik kursi-kursi kekuasaan semata-mata. Maka begitu karena sebagian besar dari anggota-anggota partai politik adalah penganggur, yang mati-matian berebut kursi kekuasaan.
Sebab kursi kekuasaan sama dengan nafkah mereka. Tak ada pula partai yang hidup dari iuran. Jadi dari mana mereka mendapat biaya hidup yang sangat besar itu? Tentu saja dari menjarah perbendaharaan nafkah bangsa. Elite politik di Indonesia adalah benalu bangsa yang rendah martabatnya. Bukan main.
Memang tidak seluruh tudingannya benar, tetapi cubitan itu cukup mewakili rasa gemas rakyat kecil yang serbanrima ing pandum alias menerima apa adanya. Pernyataan-pernyataan keras yang disampaikan dengan nuansa prosa-lirik mirip dengan puisi yang acap disetarakan ibarat lebah.
Bentuknya kecil, sengatannya mengejutkan, tetapi sesungguhnya mengandung madu yang menyehatkan. Yang juga menarik dari hampir semua karya si burung merak adalah selalu saja ada nuansa optimisme, menggugah pembaca untuk berpikir lateral, mencari alternatif. Alternatif itu tidak ada batasnya.
"The sky is the limit", begitu kata orang Barat. Remy Silado pun pernah bikin puisi mbeling: "Bila satu pintu tertutup, carilah pintu lain yang terbuka//Bila seluruh pintu tertutup, carilah jendela yang terbuka//Bila seluruh pintu, jendela dan atap, semuanya tertutup, kembalilah mencari pintu yang akan selalu terbuka, yaitu pintu doa." Nah,dalam bagian-bagian menjelang akhir dari kata pengantarnya, WS Rendra dengan arif menyampaikan pesan pamungkasnya:
"Rakyat seluruh Indonesia harus bersatu dan melakukan reformasi damai yang tuntas, melewati pengerahan persatuan dan kebangkitan bersama seluruh lokalitas-lokalitas di Nusantara, demi tegaknya daulat rakyat, daulat hukum, dan daulat ekonomi bangsa, sesuai dengan Pancasila." Bayangkan, kita semua diingatkan kembali tentang Pancasila, yang dewasa ini cenderung dilupakan.
Memeluk RembulanKendati peristiwa menyedihkan dipanggilnya Mas Willy oleh Tuhan YME terasa mendadak dan mengejutkan, tampaknya si burung merak itu sudah siap dan berancang-ancang menghadapinya dengan tegar. Kurang lebih dua bulan yang silam, awal Juni 2009, Rendra mengirim kado khusus ulang tahun ke-65 saya yang sekaligus juga hadiah untuk purna tugas sebagai pegawai negeri sipil.
Wujudnya berupa puisi dengan judul Inilah Saatnya. Bagian awal puisi tersebut amat menyentuh bila dikaitkan dengan saat-saat kepergiannya menghadap Tuhan. "Inilah saatnya// melepas sepatu yang penuh kisah// meletakkan ransel yang penuh masalah//dan mandi mengusir rasa gerah//menenangkan jiwa yang gelisah."
Mungkinkah dia sudah mendapat firasat? Wallahu a'lam bissawab. Tak ada orang yang tahu, tapi puisi itu akan mengantarnya ke keabadian. Rendra sendiri pernah mengatakan bahwa dalam sejarah umat manusia, usia puisi selalu lebih panjang ketimbang usia negara, kerajaan, atau pemerintahan.
Karya Empu Sedah lebih panjang daripada usia Kerajaan Kediri. Karya Hamsah Fansuri lebih panjang dari usia Kerajaan Iskandar Muda. Begitu juga usia karya Goethe lebih panjang daripada usia kerajaan Rusia dan usia karya Sophocles, Aristophanes, serta Emipidus juga lebih panjang ketimbang usia Yunani Athena.
Bagian akhir dari puisi Rendra yang saya jadikan judul buku antologi puisi "Inilah Saatnya" (2009), dengan sedikit improvisasi, juga menyiratkan kesiapannya "memeluk rembulan": "Inilah saatnya// menyadari kupu-kupu beterbangan// bunga-bunga di padang belantara//dan para cucu masa depan// membaca buku sejarah// mencari ilham//Inilah saatnya//Ya, saudara-saudariku//Inilah saatnya bagiku// di antara tiga Gunung// memeluk Rembulan.
Puisi-puisi Rendra mesti diakui amat menyentuh senar-senar emosi, apalagi bila diucapkan dengan penuh perasaan. Ini yang disebutkan oleh Carolyn Forche, penyair kondang asal Makedonia, dengan "a symphony of utterance, a mosaic of discreet moments of written and spoken art." Puisinya, karya tulisannya, orasi budayanya, ikut mengawal peradaban (civilization) bangsa kita yang tidak akan pernah kenal titik perhentian.
Pengakuan semacam itu tidak hanya berkumandang dalam skala nasional, melainkan juga dengan skala global. Harry Aveling dan Suzan Piper, misalnya, dalam buku "Ten Poems" yang merupakan terjemahan sepuluh puisi karya Rendra menyebutkan bahwa "Rendra is known as an electrifying reader of his works and has been invited to read his poems in many International poetry festivals: Rotterdam, Amsterdam, Berlin, Sydney, Adelaide, Tokyo, Kuala Lumpur, New Delhi, Bophal, etc". Selamat memeluk rembulan, Mas Willy, kami akan menyusulmu bila memang sudah tiba waktunya. Beristirahatlah dengan damai di surga.(*)
Prof Ir Eko Budihardjo, MscKetua Badan Penyantun Dewan Kesenian Jawa Tengah












































































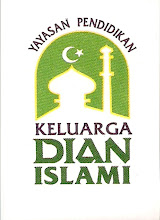
Tidak ada komentar:
Posting Komentar